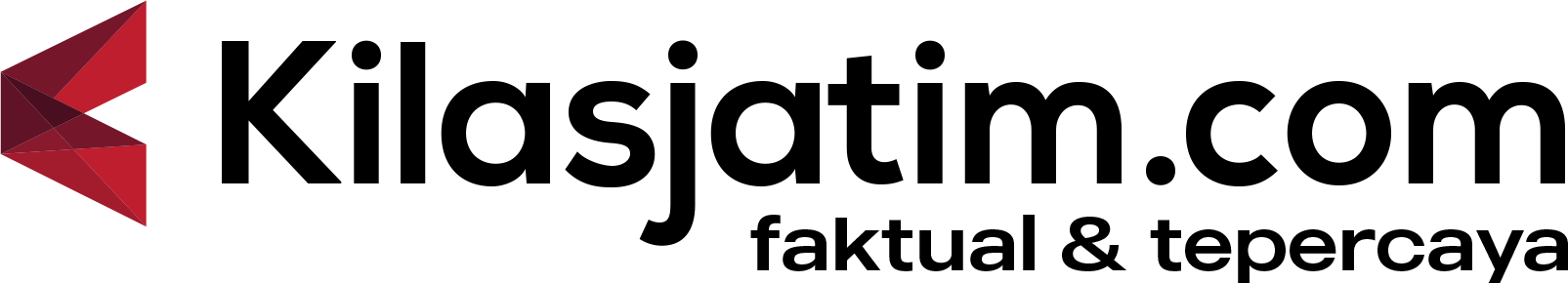Oleh M. Eri Irawan
Alumnus Magister Kebijakan Publik, Universitas Airlangga Surabaya
Tantangan terberat film bernuansa lokal (yang itu berarti keluar dari jebakan Jakarta-sentris) adalah meyakinkan banyak orang untuk datang dan menyaksikan. Tak semua berhasil, namun sebagai sebuah eksperimen yang menandai keberagaman Indonesia, film-film seperti ini sangat penting.
Dari aspek ini, “Kartolo Numpak Terang Bulan” yang disutradarai Ainun Ridho layak disambut dengan tepuk tangan yang meriah. Film ini tak hanya mengabadikan kelucuan, tapi juga menjadi etalase budaya bagi orang untuk memahami wajah masyarakat Surabaya, kota terbesar kedua di Indonesia, kota yang menjadi tulang punggung sosial ekonomi Indonesia di luar Jakarta.
Saya menyebutnya etalase budaya, karena film ini tak hanya menggunakan tuturan bahasa Jawa Arek, tapi juga melibatkan pelaku seni tradisional ludruk dan srimulat legendaris: Cak Kartolo, (alm) Cak Sapari, Ning Tini, dan (alm) Eko Tralala. Sapari dan Eko Tralala tak sempat menghadiri penayangan perdana film itu pada medio Maret ini. Sapari meninggal dunia dua tahun lalu, dan Eko menyusul setahun kemudian.
Jawa Arek sendiri adalah salah satu subkultur masyarakat Jawa, kerap diidentifikasi di wilayah Surabaya, Sidoarjo, Malang, Gresik, Mojokerto, hingga Jombang. Beberapa referensi menyebut juga di sebagian Kediri dan sebagian Blitar. Banyak yang menyebut “jantung” ideologis budaya arek berada di Surabaya. Masyarakatnya dikenal berkarakter egaliter, berani, terbuka, blak-blakan, dan punya rasa solidaritas yang tinggi.
Ludruk menjadi bagian dari budaya Jawa Arek yang khas dengan parikan jula-juli yang sering menyentil masalah sosial. Parikan pembuka yang dibawakan langsung oleh Kartolo meneguhkan posisi film ini sebagai etalase budaya.
Sebelumnya Bayu Skak juga mengajak Kartolo dan Sapari untuk terlibat dalam film “Yowis Ben”yang juga bernuansa Jawa Arek. Namun berbeda dengan “Yowis Ben”, Kartolo dan Sapari mendapat peran lebih sentral dalam alur cerita “Kartolo Numpak Terang Bulan”.
Kartolo menjadi bapak kos empat mahasiswa dari empat latar belakang kultur berbeda. Simon dari Papua, Yusuf dari Makassar, Boncel dari Malang, dan Hormat dari Tulungagung. Mereka berkawan dengan Jon, anak seorang janda bernama Tini, yang tinggal di sebelah rumah Kartolo. Sementara di depan rumah Kartolo berdirilah sebuah warung kaki lima milik Sapari dan istrinya Dewi yang menjadi tempat cangkrukan para mahasiswa itu.
Kartolo menggemari burung dan tinggal seorang diri. Ketidakhadiran keluarga dalam hidup Kartolo memunculkan tanda tanya empat anak kosnya, hingga pada suatu hari yang nahas, Kartolo pingsan dan harus dilarikan ke rumah sakit. Peristiwa ini menyingkap tabir hidup Kartolo dengan kedatangan Sari, anak perempuannya yang cantik, ke Surabaya.
Ada pada suatu masa, Kartolo, Sapari, Basman, Sokran, Blonthang, dan Tini pernah menerbitkan senyum dan meledakkan tawa warga Surabaya dan sekitarnya dengan percakapan ceplas-ceplos di atas panggung. Model percakapan seperti ini yang kemudian disalin dengan dialog-dialog lugas dalam film itu yang sukses membuat penonton tertawa.
Konsep “los-dol” dalam dialog di film itu sangat khas Surabaya. Tengok saja bagaimana Sapari melarang sang istri bercerita soal kesendirian hidup Kartolo kepada para anak kos. “Wis, wis, film e lak buyar. Gelem awakmu dibayar separuh?” katanya dengan wajah tanpa dosa.
Judul film ini saja sudah cukup untuk menggambarkan humor plesetan khas Surabaya. Orang bertanya-tanya, apa maksud judul film itu, karena terang bulan adalah nama kue di Surabaya yang dikenal kurang lebih sebagai martabak manis di Jakarta. Namun begitu melihat karakter Eko Tralala yang berperan sebagai hansip bernama Bendoyo, barulah kita tersenyum.
Sebuah film bernuansa Surabaya tentu saja tidak afdol jika tak menyinggung sepak bola. Ainun Ridho memahami itu, dan menghadirkan adegan perdebatan antara Jon dan Boncel soal rivalitas Bonek dan Aremania. Perseteruan yang akrab diperbincangkan masyarakat selama puluhan tahun itu diangkat menjadi percakapan yang egaliter, dan lagi-lagi sangat terhubung dengan kultur suporter sepak bola saat keduanya saling bilang kurang-lebih ‘Arema yang mana?’ dan ‘Bonek yang mana’ di tengah obrolan.
Kita berterima kasih kepada Ainun Ridho dan seluruh insan film dari jurusan Produksi Film SMK Dr Soetomo Surabaya (Smekdors) yang dikomandani Juliantono Hadi, yang berhasil menjadikan film ini sebagai monumen kebudayaan bagi seni ludruk dan akar sosialnya yang membentuk wajah Surabaya.
Kita juga wajib menangkupkan tangan penuh hormat seraya menyampaikan terima kasih kepada deretan nama seniman ludruk yang terlibat di film ini, dari Kartolo hingga Cak Sapari, yang telah mendedikasikan hidup untuk merawat seni tradisi ini dari generasi ke generasi. Sebuah perjalanan hidup panjang dan tak menjanjikan kemewahan: mereka tak hanya berkesenian, tapi menunaikan obligasi moral untuk menjaga apa yang telah turun-temurun diwariskan dalam kultur Jawa Arek. ()