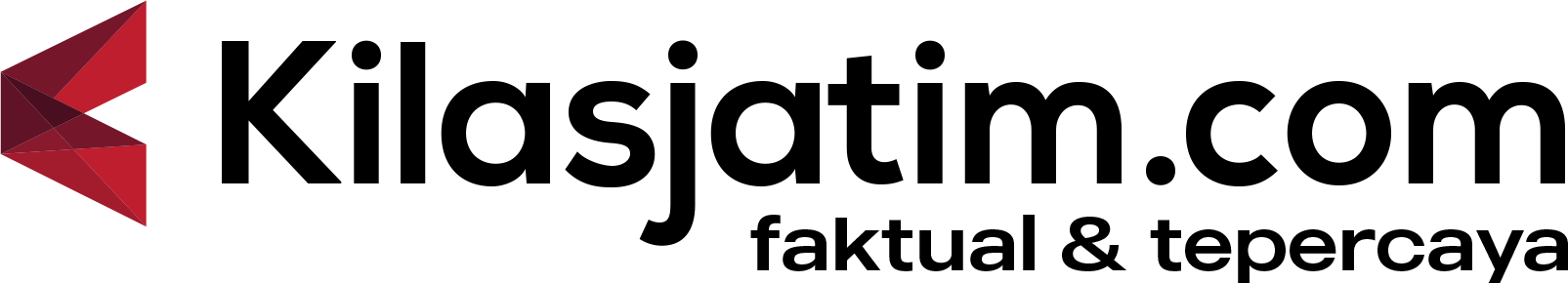Oleh Eri Irawan, penikmat film
Seorang lelaki muda berdiri di atas tembok jembatan. Sungai di bawah sana membentang di hadapannya. Orang-orang mulai panik: ini pasti mau bunuh diri.
Lelaki itu, Anto (diperankan Ardit Erwandha), adalah seorang pegawai warung tegal yang tengah frustrasi. Masa depan kisah cintanya dengan Andini (Yoriko Angeline) terancam kandas, setelah ibu sang kekasih yang diperankan pelawak Tri Retno Prayudati alias Nunung memberi syarat berat: sediakan Rp 150 juta dalam waktu sebulan.
Kata pepatah ”banyak jalan menuju Roma” jelas tak berlaku bagi Anto, sosok yang menggambarkan bagian dari 99% pemilik tabungan bank di Indonesia dengan simpanan di bawah Rp100 juta—benar, hanya ada sekira 1% orang Indonesia yang punya tabungan di atas Rp100 juta berdasar data Lembaga Penjamin Simpanan (LPS). Mau pakai cara apa untuk memperoleh Rp 150 juta dalam waktu 30 hari? Ini bukan ‘”30 hari mencari cinta”. Ini 30 hari menjaga asa agar cinta terjaga dari ”hadangan” calon mertua.
Dua sahabat Anto, Dimas (Yono Bakrie) dan Indra (Benidictus Siregar), sama miskinnya. Mereka juga terbelit urusan duit. Bersatu kita teguh? Tidak juga. Kalau tiga orang yang sama-sama dibelit urusan finansial bersatu, bukan keteguhan yang lahir, melainkan ide janggal, the power of kepepet dalam arti yang lebih gila: ritual pesugihan yang tak masuk akal.
Tentu saja karena ini cara gaib yang diselimuti ilmu hitam dan aura kegelapan, maka tiga anak manusia ini berurusan dengan demit, kuntilanak, tuyul, genderuwo, dan sebangsanya. Makhluk-makhluk halus yang seram dan sewajarnya bikin bulu kuduk merinding saat duduk di kursi sinema.
Namun tunggu dulu. ”Pesugihan Sate Gagak” adalah film komedi sejak menit pertama. Digunakannya bahasa Jawa kasar dalam dialog sepanjang film memang berisiko membuat penonton beretnis lain tidak bisa memahami kelucuannya. Seringkali subtitle tidak cukup membantu sebuah dialog berbungkus humor. Kita tahu bahwa tertawa adalah sesuatu yang kultural dan berhubungan dengan pemahaman terhadap obyek yang ditertawakan. Kelucuan dimainkan dengan simpul-simpul saraf kebudayaan.
Saya pernah menulis catatan ringan soal film bernuansa lokal serupa, “Kartolo Numpak Terang Bulan” (bisa dibaca di sini: Kartolo Numpak Terang Bulan). Tantangan terberat film bernuansa lokal (yang itu berarti keluar dari jebakan Jakarta-sentris) memang adalah meyakinkan banyak orang untuk datang dan menyaksikan. Tak semua berhasil, namun sebagai sebuah eksperimen yang menandai keberagaman Indonesia, film-film seperti ini sangat penting.
Di sinilah kepiawaian sutradara Etienne Caesar dan Dono Pradana dan penulis naskah Nuugro Agung diuji. Bahasa Jawa memang lokal. Tapi humor seharusnya universal, menembus sekat-sekat kultural. Tawa seharusnya menyatukan, bukan membingungkan dan akhirnya memisahkan.
Penulis, Eri Irawan
Dono Pradana adalah komika asal Surabaya. Maka dia mamahami benar cara untuk memancing tawa. Pilihannya untuk meletakkan Yono Bakrie dan Benidictus Siregar yang memang dianugerahi bakat melucu dalam sentral cerita tidak salah. Mereka berhasil membuat penonton tergelak. Bahkan hanya dengan penampilan, cara bicara, dan mimik muka.
Dekonstruksi Horor sampai Kritik Lingkungan
Tiga sahabat tersebut juga mendekonstruksi kengerian menjadi bahan lelucon dan kebodohan masyarakat yang percaya takhayul menjadi bahan tertawaan. Pocongan dan genderuwo pada akhirnya dihadirkan bukan untuk memberikan efek kengerian, tapi justru menjadi puncak komedi gelap tentang ketidakberdayaan manusia jika tak punya keyakinan yang kukuh.
Sesuatu yang mistis dalam film-film horor konvensional yang memenuhi jagat sinema Tanah Air beberapa tahun terakhir justru dijungkirbalikkan menjadi lelucon. Para demit dipindahkan dari
ranah ketakutan ke ranah komikal—adegan terkonyol tentu saja ketika ada bantuan tenaga medis untuk ”mengevakuasi” para demit yang merasa mual setelah melahap sate gagak bikinan Dimas dan Indra. Sebenarnya ini selaras dengan cara orang Jawa memperlakukan hal gaib: ia ditakuti, tetapi juga kerap dijadikan bahan gurauan—kita mengingat bagaimana, misalnya, kuntilanak dijadikan gurauan: susah senang selalu tertawa.
Lelucon dan kengerian di film ini juga dikemas dalam kritik cerdas soal lingkungan. Saat tiga sahabat itu menjalankan ritual pesugihan dengan membakar sate dalam posisi telanjang, lelucon cerdas dilontarkan saat Anto dan Indra melihat kemaluan Dimas: ”tipis kayak sedotan, hati-hati dimakan penyu”.
Saya teringat video peneliti Christine Figgener, yang meraih gelar doctor biologi kelautan dari Texas A&M University, kala menyelamatkan seekor penyu dengan sedotan tersangkut di lubang hidungnya—mari kita bayangkan rasa sakit yang dialami penyu itu, serupa kala hidung kita dicolok sedotan dan terus menempel entah berapa lama. Di akun Youtube Sea Turtle Biologist, video itu telah ditonton 116 juta kali dengan ratusan ribu komentar. Video menyayat hati, dengan darah yang mengucur dari hidung sang penyu ketika proses pelepasan itu dilakukan, yang seharusnya membuat kita bersumpah tidak akan lagi membuang sampah plastik sembarangan—data Badan Riset dan Inovasi Nasional: 350.000 ton sampah plastik masuk laut Indonesia (2024) dari total sampah plastik di lautan dunia sekitar 8 juta ton.
Menertawakan Hidup
Film ”Pesugihan Sate Gagak” ini juga dengan apik mampu memuat daya tahan manusia dalam kesempitan: menertawakannya lewat lelucon. Dalam tradisi Jawa, wong cilik yang berada di ambang frustasi selalu punya ruang untuk menertawakan hidup.
Dari sana kita kemudian tahu, kemiskinan memang kerap menjadi pemantik tindakan-tindakan yang nyaris tak masuk akal, termasuk pesugihan yang lahir bukan dari kejahatan, melainkan keputusasaan ekonomi. Ini kritik sosial: ketika impitan ekonomi menindih, masyarakat menengah ke bawah rentan tergelincir pada jalan pintas.
Di lain pihak, mereka juga mengkritik pola pikir feodal dan materialistis khas orang tua zaman dulu yang ada pada sosok Nunung. Sesuatu yang membuat manusia memandang manusia lainnya dengan nalar instrumental, nalar yang menganggap orang lain adalah perkakas untuk kepentingan duniawi, yang kemudian dijungkirbalikkan dengan ritual membakar harta hasil pesugihan tiga sahabat yang disarankan ”pakar supranatural” alias ”smart people” Abah Budi (Firza Valaza) untuk membersihkan pengaruh demit pada diri Anto dan kawan-kawan.
Film ini pada akhirnya bukan hanya kisah tiga sahabat kocak yang berburu Rp150 juta untuk mahar nikah Anto, duit bagi Dimas untuk membuka kios bagi ibundanya, dan uang untuk Indra agar terlepas dari jeratan pinjol—yang juga dengan cerdas disisipi kritik ”kalau tidak lunas, kakeknya akan dikirim ke Kamboja”, negara yang kini menjadi sorotan karena tindak pidana perdagangan orang dan penipuan online. Melampaui dari semua itu, film ini menghadirkan gambaran satir kelas bawah yang berhadapan dengan tekanan ekonomi, budaya takhayul yang masih mengakar, dan feodalisme keluarga.
Sebagaimana tradisi budaya Jawa, film ini sukses menjadikan dunia mistis sebagai panggung kritik kekuasaan dan membongkar kemunafikan sosial, tanpa kehilangan identitas humor yang kasar dan segar. Ia mungkin tidak universal karena lokalitasnya, tetapi justru di situlah kekuatannya: keaslian kultural di tengah mayoritas film kita yang masih Jakarta-sentris.
Jika mandat sejarah film komedi adalah membuat pecah tawa penonton sekaligus mengajak untuk berkontemplasi, maka film ini telah sukses menunaikan tugasnya dengan baik. (*)